Deskripsi
Dalam satu babak sejarah baru-baru ini, dunia hukum dan politik Indonesia diguncang oleh satu putusan yudisial yang dengan terang menunjukkan betapa rapuhnya batas antara kekuasaan dan etika institusional. Ketika konstitusi dipelintir oleh tafsir yang membuka jalan bagi aktor-aktor tertentu untuk mendekati puncak kekuasaan dengan melompati batas usia yang selama ini dijaga oleh norma hukum, maka yang kita saksikan bukan hanya keputusan hukum, tetapi juga pergeseran epistemik tentang apa yang dianggap “masuk akal”, “biasa”, bahkan “absah”. Publik dipaksa untuk menerima logika bahwa hubungan kekeluargaan antara pengambil keputusan dan penerima manfaat adalah hal yang wajar. Lebih jauh lagi, kita dihadapkan pada argumentasi legal-formal yang tampak kokoh dari luar, namun keropos secara logika moral. Peristiwa ini bukan hanya soal politik praktis, melainkan menjadi cermin besar yang mempertanyakan kembali posisi metodologi ilmu pemerintahan dalam menjelaskan dan membongkar makna etis, ontologis, serta epistemologis dari relasi antara kuasa, hukum, dan keberlanjutan demokrasi.
Kita hidup dalam sebuah era yang penuh paradoks: ketika jargon “evidence-based policy” dielu-elukan di permukaan, tetapi keberpihakan institusional justru mengabaikan jenis bukti yang tak sesuai dengan kepentingan kekuasaan. Di balik setiap narasi kebijakan yang tampak “ilmiah”, sering tersembunyi tafsir selektif atas data dan perumusan masalah yang telah dikondisikan sebelumnya. Di sinilah metodologi ilmu pemerintahan tidak boleh lagi berdiri sebagai teknik netral untuk mengevaluasi efisiensi atau mengukur kepatuhan, melainkan sebagai medan dialektika antara fakta, nilai, dan kekuasaan. Kita tidak bisa lagi hanya bertanya “apakah kebijakan ini berhasil?”, tetapi harus melangkah lebih jauh: “siapa yang didefinisikan sebagai berhasil?”, “nilai siapa yang dipakai sebagai ukuran?”, dan “epistemologi siapa yang disahkan sebagai dasar?”. Dalam lanskap pemerintahan yang terus bergeser, keberlanjutan tidak bisa lagi dimaknai sebagai kesinambungan teknokratis, tetapi sebagai ruh etis untuk memperjuangkan keadilan antargenerasi, keterbukaan makna, dan keseimbangan antara pengetahuan dan kebijaksanaan.
Buku ini lahir dari kegelisahan sekaligus komitmen untuk menjaga pijar keberlanjutan dalam arti yang paling reflektif dan radikal. Ia tidak menawarkan metodologi ilmu pemerintahan sebagai seperangkat prosedur siap pakai, melainkan sebagai medan tafsir kritis yang membuka ruang bagi pertanyaan-pertanyaan eksistensial: apa yang dianggap sebagai kebenaran dalam kebijakan publik? Bagaimana dominasi epistemik dapat diselipkan melalui angka, grafik, atau indeks yang tampak objektif? Dan sejauh mana aktor-aktor pemerintahan sadar akan posisi mereka sebagai pembentuk realitas, bukan hanya pelaksana teknis? Keberlanjutan, dalam kerangka ini, bukan sekadar proyeksi jangka panjang, melainkan komitmen untuk tidak memutus relasi antara manusia, pengetahuan, dan dunia. Dan metodologi ilmu pemerintahan harus menjadi jembatan yang menjaga relasi itu tetap hidup, terbuka, dan penuh keberanian.

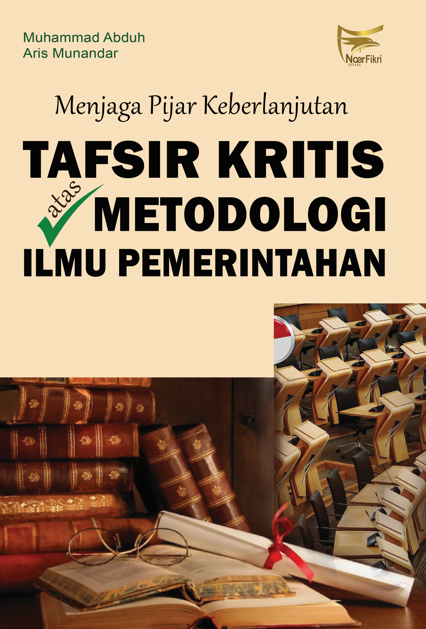
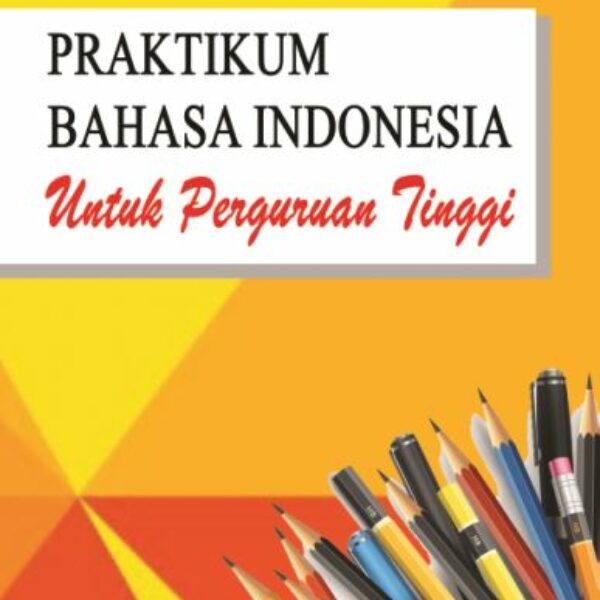

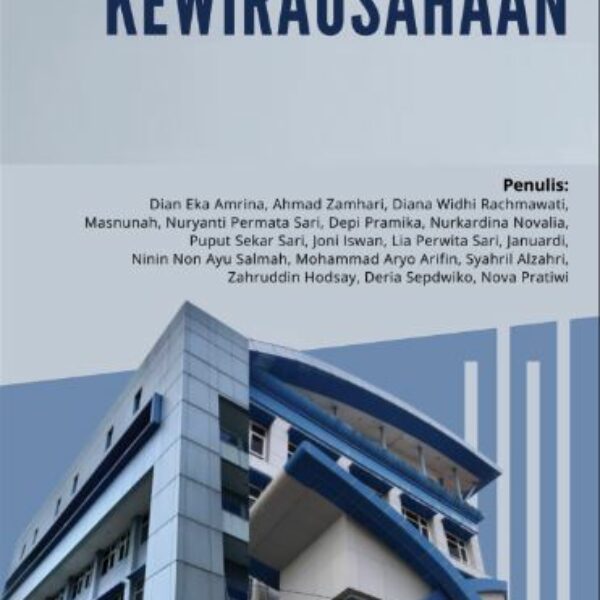
Ulasan
Belum ada ulasan.