Deskripsi
Tak banyak yang menyangka bahwa data dari desa-desa terpencil di Indonesia dapat menjadi fondasi dari riset ilmiah yang kelak meraih Penghargaan Nobel Ekonomi. Namun demikianlah kenyataannya. Pada tahun 2019, Esther Duflo, bersama Abhijit Banerjee dan Michael Kremer, dianugerahi Nobel atas pendekatan eksperimental mereka dalam memahami dan mengurangi kemiskinan global. Salah satu studi paling berpengaruh yang melandasi penghargaan ini adalah penelitian Duflo (2001) mengenai dampak jangka panjang program SD Inpres di Indonesia—sebuah inisiatif pembangunan sekolah dasar berskala nasional yang diluncurkan pada dekade 1970-an. Yang menjadi sorotan bukan semata substansi kebijakannya, tetapi bagaimana Duflo mengungkap efek jangka panjang dari kebijakan tersebut melalui analisis cermat terhadap data statistik yang dihimpun oleh negara, yakni PODES (Potensi Desa) dan Sakernas (Survei Angkatan Kerja Nasional).
Melalui metodologi natural experiment, Duflo menunjukkan bahwa statistik pemerintahan, jika digunakan secara teliti dan etis, dapat melampaui peran deskriptifnya dan menjadi alat pengungkap relasi kausal yang membentuk kemiskinan dan ketimpangan. Ini bukan sekadar temuan teknis, melainkan pelajaran epistemologis yang mendalam: bahwa statistik yang sering dianggap netral dan teknokratis, pada hakikatnya dapat menjadi medan perjuangan makna, refleksi kebijakan, dan bahkan instrumen transformasi sosial. Dalam konteks itu, Duflo tidak memperlakukan data sebagai cermin pasif dari kenyataan, melainkan sebagai jendela yang membuka jalan bagi keadilan kebijakan yang lebih tajam dan terukur.
Buku ini lahir dari kesadaran akan ironi yang mencolok: data yang digunakan untuk meraih Nobel bukanlah data eksklusif yang hanya tersedia di laboratorium ilmiah negara maju, melainkan data resmi yang dihimpun oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia—lembaga negara yang sering kali direduksi hanya sebagai produsen angka. Jika diperlakukan secara kritis, statistik pemerintahan dapat menjadi lebih dari sekadar laporan berkala; ia dapat menjadi fondasi keberlanjutan sosial yang adil dan inklusif. Sayangnya, potensi besar ini sering tidak dioptimalkan akibat keterbatasan visi, dominasi paradigma positivistik, serta kurangnya keterbukaan sistemik dalam pemerintahan dan tata kelola data.
Oleh karena itu, buku ini merupakan refleksi kritis terhadap bagaimana statistik diproduksi, dikategorikan, dimaknai, dan dipergunakan dalam sistem pemerintahan. Kata “menciptakan” dalam judul bukan sekadar diksi puitik, melainkan sikap epistemologis yang menegaskan bahwa keadilan sosial tidak muncul otomatis dari angka, melainkan dari cara angka-angka tersebut dibentuk, ditafsirkan, dan diarahkan. Dalam kerangka itu, keberlanjutan tidak hanya soal keberlangsungan lingkungan atau ekonomi, melainkan juga tentang keberlangsungan etika dan tanggung jawab dalam memaknai data publik.

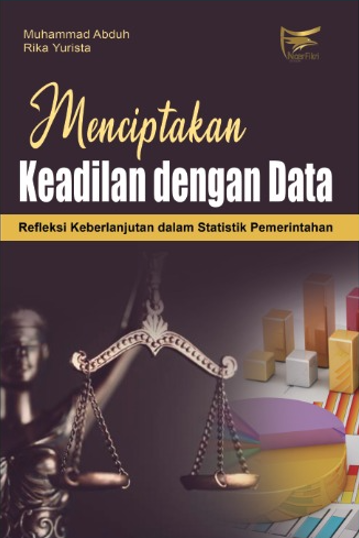
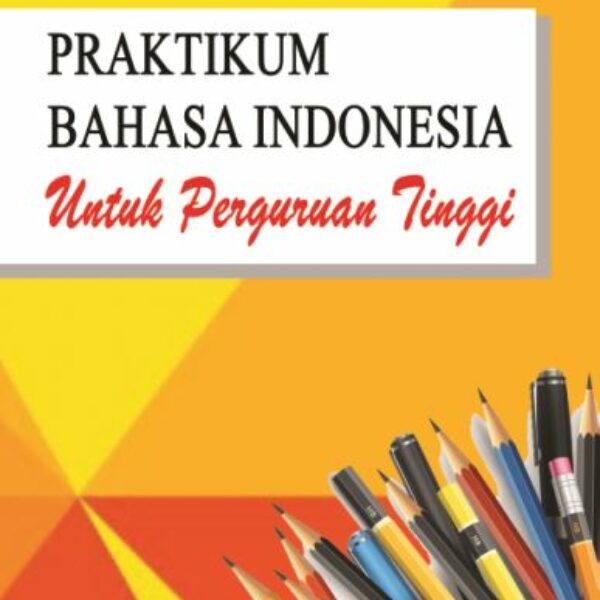


Ulasan
Belum ada ulasan.